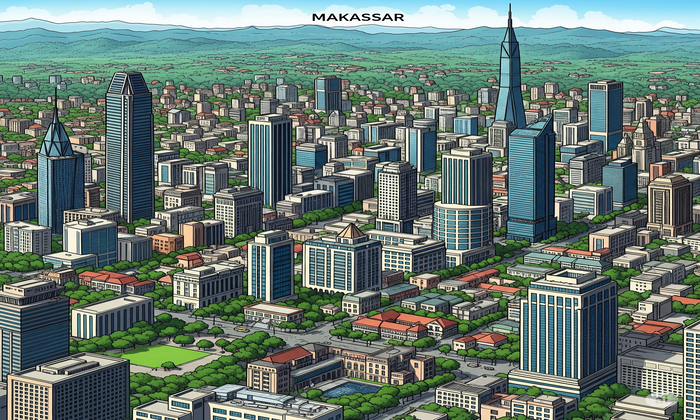MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Siang itu, Maulana Ishak menatap matahari dari balik jendela rumahnya di Mariso. Udara terasa tajam, menampar kulit tanpa ampun. Sinar mentari mencuat garang di antara bangunan tinggi dan proyek konstruksi yang tak kunjung selesai. Debu-debu melayang di udara seperti serbuk yang kehilangan arah pulang.
Ia mengurungkan niat keluar rumah. Di luar, kota terasa bukan lagi miliknya.
“Belakangan ini terasa cukup buruk,” ujarnya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri.
Di masa lalu, Makassar menyuguhkan keteduhan yang akrab. Di jalan-jalan kecilnya, pohon besar tumbuh sebagai payung hidup, menawarkan ketenangan dan perlindungan dari panas. Tapi pohon-pohon itu kini tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah batang kurus yang tumbuh ragu di antara trotoar sempit, atau akar tua yang menyembul dari bekas taman yang dijadikan parkiran.
Baca juga: Eco-anxiety : Anak Muda Makassar dan Kecemasan Iklim
“Sekarang marak penebangan. Pohonnya masih ada, tapi sudah tak seperti dulu,” kata Maulana.
Ia bukan sekadar mengeluh tentang panas. Ia sedang menggambarkan rasa kehilangan—pada suasana, pada lanskap, pada makna kota itu sendiri. Bagi Maulana, perubahan bisa dilihat dari hal-hal kecil. Seperti langit yang tak lagi bersih. Seperti burung-burung kecil yang dulu sering mampir di ranting jendela, kini tak pernah lagi terdengar suaranya.
Baca juga: Makassar dalam Krisis: Jalan Panjang Menuju Kota Ramah Iklim
“Mungkin karena habitatnya hilang,” ia menambahkan, pelan.
Sebagai mahasiswa pascasarjana yang terbiasa bergumul dalam ruang-ruang diskusi, Maulana tahu, ini bukan sekadar isu iklim. Ini adalah soal keberpihakan. Pembangunan, baginya, sudah lama condong pada satu sisi. Gedung-gedung tumbuh seperti jamur setelah hujan, tapi yang mengering justru ruang hidup bagi warga biasa.
“Pembangunan kota hanya menguntungkan segelintir kelompok,” ujarnya, dengan nada datar.
Kata-kata seperti penghijauan dan ruang terbuka hijau sering ia dengar. Dari seminar, dari media, dari kampanye yang singgah lalu lenyap. Tapi yang ia saksikan di jalan hanyalah beton dan aspal, yang perlahan melapisi setiap inci tanah.
“Kampanye ruang hijau masif kita dengarkan, tapi tidak jelas realisasinya,” katanya.
Namun Maulana bukan sepenuhnya pesimis. Di sela kota yang memanas, ia masih melihat secercah harapan: taman kota. Setiap akhir pekan, taman-taman yang tersisa menjadi tempat perhentian orang-orang yang ingin bernapas. Anak-anak berlarian di antara ilalang, pasangan muda duduk di bawah pohon kecil yang tumbuh sepi, dan para lansia berjalan perlahan menyusuri jalur pejalan kaki.
“Itu satu-satunya oase kecil di tengah sesaknya Makassar,” ucapnya.
Makassar, kota yang tumbuh lebih cepat dari bayangannya sendiri, seperti rumah yang direnovasi tanpa memperhitungkan penghuninya. Tapi Maulana tak ingin menyerah. Ia tahu kota ini bisa lebih baik, jika yang dibangun bukan sekadar dinding dan jalan tol, melainkan perasaan aman dan nyaman bagi warganya.
“Kita butuh pembangunan yang memihak manusia, bukan hanya beton,” tutupnya.
Kendati dalam lima tahun terakhir, ruang terbuka hijau (RTH) di Makassar bertambah. Tapi bagi Slamet Riyadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan, pertambahan itu tidak menandakan kemajuan.
“Kenaikannya tidak signifikan,” katanya. “Ketimbang laju pengurangan ruang terbuka hijau sendiri.”
Menurut Slamet, persentase RTH Makassar naik dari 9 persen menjadi 12 persen. Tapi di sisi lain, ia melihat penurunan ruang hijau berjalan lebih cepat.
“Memang ada pertambahan,” katanya, “tapi penurunannya juga besar.”
Ia menyebut, situasi ini membuat tren pertumbuhan ruang hijau seolah stagnan. Kenaikan angka tidak mencerminkan perbaikan kondisi ekologis di lapangan.
Salah satu contoh nyata adalah Taman Macan. Di area itu, ruang terbuka hijau yang semula ada, kini sebagian diambil alih untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik. Meskipun tidak sepenuhnya diambil, tapi tetap saja menggantikan pohon tua dengan pohon muda.
“Itu sudah tidak sebanding,” kata Slamet.
Baginya, kehilangan satu pohon dewasa di ruang kota tidak bisa diimbangi dengan penanaman pohon muda.
Makassar, Kota yang Makin Terbangun
Secara spasial, menurut WALHI, sekitar 64 persen lahan Kota Makassar sudah terbangun. Bangunan-bangunan ini, kata Slamet, didominasi aspal dan beton.
“Secara ekologis, ketika hujan turun, airnya tidak bisa meresap ke dalam tanah,” ujarnya.
Air permukaan hanya mengalir tanpa kesempatan diserap bumi, atau dalam istilah hidrologi: run off. Dampaknya adalah berkurangnya kemampuan alami kota menyerap dan mengolah air.
Ruang hijau yang seharusnya menjadi pemecah masalah justru ikut menyusut. Bukan hanya di ruang publik, tapi juga dalam kawasan perumahan. Dalam aturan, setiap kawasan hunian seharusnya menyediakan 30 persen area untuk RTH. Tapi Slamet menyebut kenyataan di lapangan jauh dari ketentuan itu. “Yang kami lihat tidak sampai 30 persen,” katanya.
Alasannya klasik: permintaan rumah semakin tinggi. Maka, lahan yang seharusnya diplot sebagai ruang hijau, berubah fungsi menjadi unit rumah baru.
“Itu masalah juga,” katanya.
RTH yang dikorbankan demi pertumbuhan properti membuat ruang kota makin sesak, tanpa ruang bernapas bagi warganya.
Ketika Pesisir Mulai Padat
Masalah lain datang dari arah pesisir. Slamet menyebut, pembangunan massif di kawasan pesisir Kota Makassar sudah berlangsung sejak reklamasi Center Point of Indonesia (CPI).
“Itu awal mulanya pembangunan massif di kota,” katanya.
Ia menyampaikan kekhawatiran: kawasan pesisir yang seharusnya menjadi penyangga ekologis kini padat bangunan.
Pembangunan yang tak mengindahkan keberadaan ruang hijau, menurutnya, telah menyumbang degradasi kualitas lingkungan hidup kota.
“Ada kekhawatiran melihat massifnya pembangunan di pesisir,” kata Slamet. Kota tumbuh, tapi tidak dengan ruang hijau yang cukup untuk menyeimbangkan.
Koordinasi yang Lemah, Pengawasan yang Longgar
Menurut Slamet, ada kelemahan koordinasi dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau, terutama di kawasan perumahan. Regulasi boleh ada, tapi implementasinya lemah.
“Aturannya jelas,” katanya, “tapi pengawasan sering kali longgar.”
Dalam catatan WALHI, lemahnya pengawasan membuat penyusutan RTH di Makassar tidak terdeteksi secara real-time. Maka ketika kota sadar ruang hijaunya makin sedikit, semuanya sudah terlambat.
CPI dan Pesisir yang Tergerus
Bagi Slamet Riyadi, proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) menjadi titik awal perubahan besar-besaran lanskap pesisir Kota Makassar. Reklamasi ini, katanya, bukan sekadar soal penambahan daratan, tapi juga simbol dominasi politik ruang yang mengundang gelombang pembangunan lain.
“Karena ada CPI, ada banyak hotel yang berdiri, ada banyak perumahan, ada kafe-kafe dan restoran,” ujarnya.
Beban lingkungan pun bertambah. Bangunan-bangunan baru di kawasan pesisir berdiri tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. “Beberapa pembangunan tidak memperhatikan persoalan lingkungan hidup,” kata Slamet.
Ia menyebut soal sempadan pantai—wilayah yang seharusnya dilindungi dan bebas dari aktivitas manusia.
“Sempadan itu daerah yang menjorok lurus ke laut… reklamasi seharusnya tidak berada di situ,” tegasnya.
Sebelum dibangun, wilayah pesisir itu juga ditumbuhi mangrove yang kini hilang. CPI banyak mengubah lanskap wilayah pesisir Kota Makassar. Tidak hanya di pantainya, tetapi juga di daratan.
Dari Izin yang Belum Terbit, Hingga Pasir yang Ditambang
Pelanggaran sudah tampak sejak awal pembangunan. Slamet menyebut bahwa proyek reklamasi CPI dijalankan tanpa izin lengkap. Belum dapat izin pemanfaatan ruang dari KKP, Menteri, tapi sudah direklamasi. Bahkan, menurutnya, Menteri sempat melarang pembangunan dilanjutkan sebelum ada izin.
“Tapi lagi-lagi ada tekanan politik dari oligarki,” ujarnya. Slamet menyebut proyek ini dijalankan oleh pihak swasta, yakni Ciputra Group.
Tak hanya soal izin lokasi, sumber material reklamasi pun bermasalah. Slamet mengatakan tambang pasir laut yang digunakan untuk CPI diambil dari wilayah yang dekat dengan pemukiman nelayan di Galesong.
“Itu sudah melanggar juga,” katanya.
Kota Tanpa Nafas, Air Tanpa Rasa
Dampaknya kini dirasakan masyarakat. Slamet menyebut ada tiga hal pokok yang tergerus akibat penyusutan ruang terbuka hijau. Pertama, polusi. “Pohon-pohon itu dapat menyerap polusi,” katanya. Tapi saat RTH kurang dan kendaraan terus bertambah, emisi karbon meningkat tanpa penyerap alami.
Kedua, banjir. Tanpa ruang hijau, kota kehilangan daya serap air.
“Kalau tidak ada RTH, kemungkinan besar banjir akan sangat cepat terjadi,” ujar Slamet.
Ketiga, krisis air bersih. Ia menyebut cadangan air tanah di Makassar mulai terganggu.
“Di beberapa daerah ditemukan infiltrasi air laut,” katanya. Dampaknya: air sumur warga yang dulu tawar, kini perlahan menjadi asin, keruh, dan berbau.
Ketika Suara Dilibatkan, Tapi Tak Didengar
WALHI Sulsel, kata Slamet, sebenarnya sudah dilibatkan dalam sejumlah diskusi. Namun keterlibatan itu hanya sebatas forum. Namun, kalau pelibatannya dalam hal menyusun perencanaan, kata dia, itu belum ada.
“Kami hanya diundang sebagai pembicara,” ujarnya.
Sebab itu, WALHI terus mengkampanyekan isu RTH secara mandiri. Slamet menegaskan, ruang terbuka hijau bukan pelengkap tata kota. RTH, kata dia, adalah salah satu variabel yang penting untuk membuat suatu kota bisa bertahan dan melawan arus perubahan iklim. Tanpa RTH, katanya, secanggih apa pun infrastruktur, kota akan runtuh.
“Kalau tidak,” kata Slamet, “perlahan kota ini binasa.” (Andi/IN)