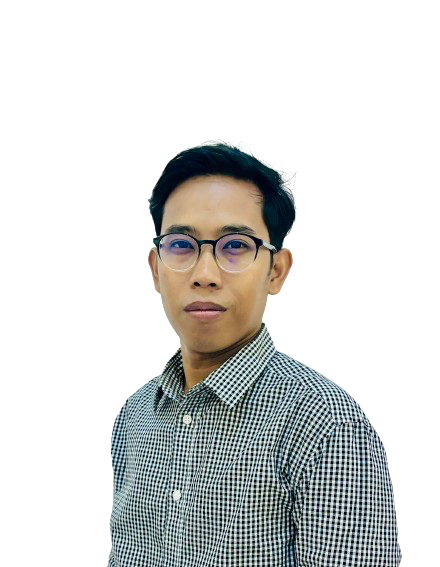DI setiap pesta demokrasi, istilah “serangan fajar” menjadi momok yang akrab terdengar. Praktik politik uang ini sering dilakukan menjelang hari pemilihan, di mana kandidat atau tim sukses mereka memberikan uang, barang, atau bantuan lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih.
Meski sudah jelas melanggar hukum, praktik ini tetap berlangsung, bahkan di era modern dengan pengawasan yang lebih ketat. Fenomena ini tidak hanya sekadar pelanggaran etika, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekuasaan dan kendali ideologis bekerja di tengah masyarakat. Wacana ini pun berkembang pesat di momen Pilkada Serentak 2024 di Indonesia, khususnya di Sulsel.
Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxist asal Italia, memperkenalkan konsep hegemoni sebagai cara kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya bukan hanya melalui paksaan (force), tetapi juga melalui persetujuan (consent). Persetujuan ini dibangun lewat dominasi ideologi, budaya, dan institusi masyarakat sipil seperti media, pendidikan, dan agama.
Dalam konteks “serangan fajar,” praktik ini menjadi alat bagi kandidat untuk membangun legitimasi palsu. Dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat, mereka menciptakan kesan bahwa bantuan materi adalah tanda perhatian, padahal ini hanya taktik manipulasi demi mempertahankan dominasi politik.
Memanfaatkan Ketimpangan Ekonomi
Sulawesi Selatan, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi. Banyak masyarakat yang bergantung pada penghasilan harian, membuat mereka rentan terhadap iming-iming uang atau bantuan barang. Dalam situasi ini, “serangan fajar” memanfaatkan kondisi ekonomi untuk menciptakan loyalitas semu.
“Kami terima uangnya, tapi tidak tahu mau pilih siapa. Toh, bantuan seperti ini belum tentu datang lagi kalau mereka terpilih,” ujar seorang warga di Makassar. Pernyataan ini menunjukkan dilema moral yang dihadapi masyarakat, di mana kebutuhan mendesak sering mengalahkan idealisme demokrasi.
“Untuk mengetahui yang mau menerima itu, lihat dari kendaraan yang ada di parkirannya. Jika punya mobil, itu tidak akan mengubah pilihannya, jika mempunyai dua motor diambil tapi standarnya Rp300 ribu, kalau satu motor dan tidak punya kendaraan, berapa pun diambil. Belum lagi dibagi atas basis suara,” beber seorang akademisi di Makassar.
Kutipan tersebut, menguatkan bahwa wacana tersebut “serangan fajar” memanfaatkan ketimpangan ekonomi.
Budaya Balas Budi
Di banyak wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, budaya patronase masih kuat. Dalam budaya ini, kandidat dipandang sebagai “pemberi” yang dermawan, sementara masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk membalas budi melalui suara mereka. Budaya ini memperkuat hegemoni kandidat, membuat praktik politik uang diterima secara sosial.
Belum lagi, media berperan penting dalam membentuk opini publik. Kandidat dengan sumber daya besar sering menggunakan media untuk membangun citra positif, bahkan ketika mereka terlibat dalam praktik “serangan fajar.” Di sisi lain, media independen dapat menjadi alat perlawanan dengan mengungkap dampak buruk dari politik uang.
Namun, di era digital, praktik “serangan fajar” telah bertransformasi. Bantuan tidak lagi hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga bisa berupa promosi melalui influencer, program sosial dadakan, atau narasi manipulatif di media sosial. Ini menunjukkan bahwa hegemoni telah beradaptasi dengan zaman.
Dampak
Praktik “serangan fajar” memiliki dampak serius bagi demokrasi, pertama menghambat kualitas pemimpin. Kandidat yang fokus pada politik uang cenderung tidak memiliki visi dan misi yang jelas untuk masyarakat. Kedua, merusak Integritas demokrasi. Pemilu menjadi ajang transaksi, bukan seleksi pemimpin terbaik.
Namun, perlawanan terhadap hegemoni ini sedang berlangsung. Kampanye anti-politik uang yang dilakukan oleh masyarakat sipil, media, dan organisasi lokal mulai menunjukkan hasil. Di beberapa wilayah, pemilih muda yang lebih sadar mulai menolak politik uang dan memilih berdasarkan integritas kandidat.
Melawan “serangan fajar” bukan hanya soal menolak uang atau barang, tetapi juga soal membangun budaya politik yang sehat. Edukasi pemilih, terutama di kalangan muda, menjadi kunci untuk menghancurkan hegemoni yang telah lama mengakar.
“Serangan fajar” adalah bentuk nyata bagaimana hegemoni kekuasaan bekerja di tingkat lokal. Namun, hegemoni tidak bersifat abadi. Dengan kesadaran kolektif, resistensi dari masyarakat sipil, dan peran media yang berpihak pada integritas, praktik ini dapat dilawan. Sulawesi Selatan, dengan kekayaan budayanya, memiliki potensi besar untuk memimpin gerakan ini, menciptakan demokrasi yang lebih bersih dan adil. (***)